Muhamad Chatib Basri : Fiskal dan Pertumbuhan
Sejarah, barangkali adalah sebuah catatan murung tentang pertikaian, tentang rivalitas dan tentang penaklukan. Termasuk pertikaian antara kekuatan yang baru muncul dengan kekuatan yang telah mapan.
Sejarawan Yunani Kuno, Thucydides, pernah menulis bagaimana perang Peloponnesian pecah karena kekuatan Athena yang semakin kuat menimbulkan kekuatiran pihak Sparta. Ketegangan antara China dengan Amerika Serikat (AS) adalah pengulangan sejarah ini. Akademisi dari Harvard, Graham Allison, menyebutnya Thucydides trap (perangkap Thucydides).
Ketegangan antara China dengan AS, memang bukan sekadar perang dagang. Ia adalah kekuatiran AS akan semakin berkembangnya dominasi China. Karena itu, tampaknya kita harus bersiap untuk sebuah ketegangan yang panjang. Dan ekonomi dunia pun merasakan dampaknya. Di Asia, Singapura hanya tumbuh 0,5 persen, Thailand 2,35 persen dan Malaysia 4,37 persen. Dari segi ini Indonesia masih cukup baik. Kita masih bisa tumbuh 5,02 persen di triwulan ke tiga 2019. Namun tentu kita tidak bisa menutup mata: Vietnam dan Filipina masing-masing tumbuh 7,31 persen dan 6,18 persen, lebih baik dari kita.
Penurunan harga komoditas dan tambang akibat perlambatan ekonomi China berdampak kepada kita. Kita masih beruntung, walau sedikit melambat, konsumsi rumah tangga masih bisa tumbuh 5 persen. Dan konsumsi adalah penopang utama Produk Domestik Bruto (PDB) kita saat ini. Fenomena konsumsi rumah tangga yang relatif ajek pernah di jelaskan oleh ekonom James Duesenberry dalam bukunya Income, Saving and the Theory of Consumer Behavior yang terbit tahun 1949. Ia menulis: konsumsi kita tidak hanya ditentukan oleh pendapatan saat ini, tetapi juga oleh pola konsumsi kita di masa lalu.
Ketegangan antara China dengan AS, memang bukan sekadar perang dagang. Ia adalah kekuatiran AS akan semakin berkembangnya dominasi China. Karena itu, tampaknya kita harus bersiap untuk sebuah ketegangan yang panjang.
Contoh paling sederhana: seseorang penggemar kopi yang baik akan sulit untuk mendadak menurunkan konsumsi kopinya ke kualitas yang lebih rendah ketika pendapatannya turun. Konsumsi mudah naik, tetapi tak mudah turun.
Di sisi lain kita mencatat: penerimaan pajak jatuh. Data Kementerian Keuangan menunjukkan, periode Januari-Oktober 2019 total penerimaan pajak hanya tumbuh 0,23 persen dibandingkan periode sama 2018. Pajak penghasilan non migas sendiri hanya tumbuh 3,3 persen, sedangkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam negeri, yang mencerminkan daya beli, malah mengalami pertumbuhan negatif (-2,42 persen). Data-data ini menguatkan bahwa perlambatan ekonomi sedang terjadi.
Kebijakan fiskal kontra-siklus
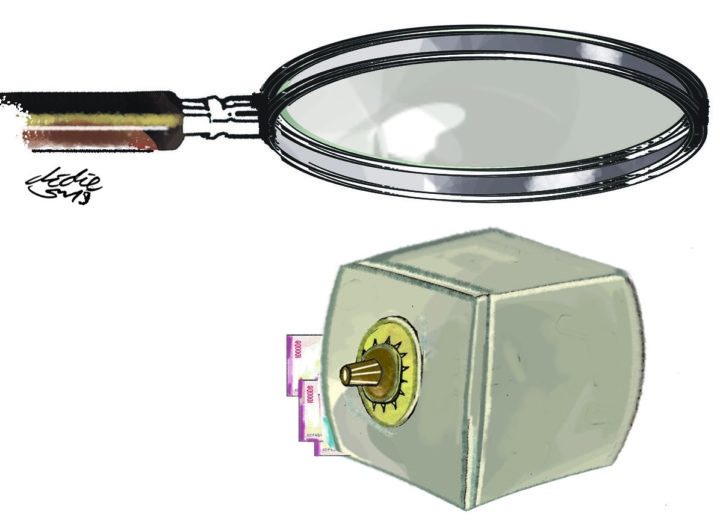 Lalu apa yang bisa dilakukan untuk mengantisipasinya? Bank Indonesia memang sudah menurunkan tingkat bunga 100 basis poin. Sayangnya penurunan tingkat bunga tak mendorong investasi secepat yang diharapkan. Malah kredit yang tak dicairkan (undisbursed loan) per September 2019 mengalami peningkatan 5,07 persen dibandingkan periode sama 2018. Fenomena ini mengingatkan saya pada apa yang ditulis ekonom John Maynard Keynes 90 tahun lalu: permintaanlah yang mendorong produksi.
Lalu apa yang bisa dilakukan untuk mengantisipasinya? Bank Indonesia memang sudah menurunkan tingkat bunga 100 basis poin. Sayangnya penurunan tingkat bunga tak mendorong investasi secepat yang diharapkan. Malah kredit yang tak dicairkan (undisbursed loan) per September 2019 mengalami peningkatan 5,07 persen dibandingkan periode sama 2018. Fenomena ini mengingatkan saya pada apa yang ditulis ekonom John Maynard Keynes 90 tahun lalu: permintaanlah yang mendorong produksi.
Jika permintaan terhadap barang dan jasa lemah, untuk apa dunia usaha meminta kredit dan melakukan ekspansi produksi? Walaupun perizinan dipermudah, jika permintaan tidak ada, untuk apa melakukan ekspansi bisnis? Implikasinya: penyederhanaan perizinan, revisi UU Ketenagakerjaan, penurunan suku bunga tidak akan serta merta mendorong perekonomian. Dalam jangka pendek, peningkatan konsumsilah yang akan mendorong produksi. Itu sebabnya kita perlu kebijakan fiskal yang kontra- siklus. Masalahnya, dengan kondisi penurunan penerimaan pajak, ruang fiskal terbatas. Lalu apa yang bisa dilakukan? Ada beberapa hal yang bisa dilakukan.
Pertama, studi saya dan Sjamsu Rahardja dari Bank Dunia (2011) menunjukkan kebijakan fiskal kita cenderung bersifat pro-siklus. Artinya, ketika penerimaan pajak turun karena perlambatan ekonomi, pemerintah cenderung melakukan penghematan. Padahal kita butuh belanja yang lebih besar untuk mendorong perekonomian. Karena itu, amat wajar jika pemerintah meningkatkan defisit anggaran, dan bahkan mendorong belanja. Defisit anggaran diperkirakan akan mencapai 2,2 persen tahun ini. Menurut saya, menaikkan defisit anggaran sampai 2,5 persen pun tak apa-apa untuk dorong perekonomian.
Dalam jangka pendek, peningkatan konsumsilah yang akan mendorong produksi. Itu sebabnya kita perlu kebijakan fiskal yang kontra- siklus
Tentu kita tetap harus hati-hati bila defisit anggaran terlalu tinggi. Mengapa? Ada risiko crowding out. Apa maksudnya? Defisit anggaran yang lebih besar harus dibiayai dengan mengeluarkan Surat Utang Negara atau obligasi. Karena imbal hasil dari obligasi pemerintah lebih menarik ketimbang bunga deposito, terjadi perpindahan tabungan dari perbankan ke obligasi pemerintah. Akibatnya sumber untuk ekspansi kredit di perbankan menjadi terbatas. Implikasinya: investasi swasta mandek atau melambat.
Yang menarik, hubungan antara defisit anggaran dan likuiditas perbankan tak linier. Sampai tingkat tertentu, pembiayaan defisit melalui obligasi domestik berpengaruh positif ke pertumbuhan dana pihak ketiga di perbankan, karena orang memiliki pilihan investasi. Namun setelah melewati tingkat tertentu, ia akan menyerap dana pihak ketiga di perbankan. Kesimpulannya: defisit anggaran memang dibutuhkan untuk mendorong permintaan domestik, namun harus dijaga pada tingkat yang optimal.
Kedua, jika sumber dana domestik terbatas, mengapa kita tak mengambil sumber dana dari luar negeri saja? Di sini saya harus mengingatkan: jika pasar obligasi pemerintah didominasi investor asing, ekonomi Indonesia akan rentan kepada gejolak arus modal. Peningkatan defisit anggaran akan meningkatkan defisit transaksi berjalan karena kesenjangan tabungan dan investasi meningkat. Bila kenaikan defisit transaksi berjalan ini sebagian besar dibiayai portofolio, maka setiap kali terjadi kejutan di luar negeri pasar keuangan akan bergejolak dan rupiah akan terpukul.
Di sini saya harus mengingatkan: jika pasar obligasi pemerintah didominasi investor asing, ekonomi Indonesia akan rentan kepada gejolak arus modal.
Perbaikan kualitas belanja
Ketiga, dengan kendala fiskal seperti itu, pemerintah harus fokus kepada perbaikan kualitas belanja. Harus dipastikan bahwa belanja yang dikeluarkan memiliki dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Studi yang dilakukan oleh Joppe de Ree, Karthik Muralidharan, Menno Pradhan dan Halsey Rogers (2017) menunjukkan: tunjangan profesi guru tidak berdampak kepada perbaikan kualitas pendidikan, padahal jumlahnya sangat besar.
Contoh lain, transfer untuk pemerintah daerah. Kita tahu dana yang mengendap di rekening kas umum daerah begitu besar, sehingga tak memberikan dampak kepada pertumbuhan ekonomi. Alokasi belanja untuk berbagai kementerian tentu perlu dilihat mana yang prioritas dan punya dampak kepada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Ini penting, karena Basri dan Rahardja (2011) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di luar gaji dan subsidi sebenarnya bersifat kontra siklus. Apa artinya? Jika kualitas belanja diperbaiki dengan mengalokasikan anggaran lebih banyak kepada belanja di luar gaji dan subsidi (misalnya belanja modal), maka kebijakan fiskal menjadi kontra-siklus.
Keempat, ketika permintaan telah terjadi maka dunia usaha akan meresponsnya dengan meningkatkan produksi. Untuk meningkatkan produksi, dunia usaha perlu bunga yang rendah, izin yang mudah, dan berbagai deregulasi ekonomi. Karena itu kita harus melihat kebijakan ini secara lengkap.
Kelima, kita tahu bahwa ruang fiskal kita terbatas. Walau dalam jangka pendek kebijakan fiskal harus bersifat kontra-siklus, dalam jangka menengah panjang, fiskal harus dijaga agar berkesinambungan. Dalam kondisi seperti ini, penerimaan pajak harus ditingkatkan. Tapi ini tidak mungkin dilakukan dengan meningkatkan tarif pajak atau mengejar pembayar pajak yang patuh. Kenapa? Karena ini akan membuat perekonomian kian mengalami kontraksi.
Lalu bagaimana? Risalah saya bersama Ben Olken, Mayara Felix dari Massachusetts Institute of Technology (MIT) dan Rema Hanna dari Harvard, di National Bureau Economic Research (NBER) (2019), menunjukkan: untuk setiap kenaikan satu rupiah peningkatan tarif pajak, wajib pajak akan mendapatkan beban tambahan lagi sebesar 0,51 rupiah. Karena itu harus dipikirkan jalan lain yang tak membebani wajib pajak tapi tetap menaikkan total penerimaan pajak pemerintah. Caranya adalah perbaikan administrasi perpajakan dengan memindahkan pelayanan badan usaha dari kantor pajak reguler ke Kantor Pajak Madya (MTO). Mengapa?
Karena itu harus dipikirkan jalan lain yang tak membebani wajib pajak tapi tetap menaikkan total penerimaan pajak pemerintah. Caranya adalah perbaikan administrasi perpajakan dengan memindahkan pelayanan badan usaha dari kantor pajak reguler ke Kantor Pajak Madya (MTO).
Kami menduga bahwa keterbatasan sumber daya di kantor pajak reguler membuat mereka cenderung memfokuskan diri pada beberapa wajib pajak dengan potensi pendapatan yang tinggi. Akibatnya, badan usaha yang besar akan menjadi sasaran. Ada kemungkinan mereka akan semakin menghindar membayar pajak seiring pertumbuhan skala perusahaannya. Bila dipindahkan ke MTO, dengan jumlah staf yang lebih banyak, perlakuan terhadap badan usaha menjadi lebih seragam. Beban pajak tak hanya “ditanggung” beberapa perusahaan yang besar. Akibatnya mereka tetap bisa bertumbuh dan membayar pajak.
Ironis, ekonomi dunia harus membayar ketegangan antara China dengan AS. Sejarah memang selalu berulang. Dan kita mencatanya dengan murung. Teringat saya pada sastrawan Albert Camus yang menulis dengan getir: jika ada bagian paling penting dari sejarah manusia harus ditulis, itu adalah catatan tentang penyesalan dan ketidakmampuan. Camus mungkin terlalu murung.
Muhamad Chatib Basri, Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.
Sumber : Harian Kompas, 05 Desember 2019

